Fenomena Politik Pendidikan Gelar Akademik Dan Buah Mojo
Terkesan
saya membaca essay Ardhie Raditya yang publish di kolom opini JawaPos.com dengan
judul Doktor Dagelan dan Politik Gila Gelar, pada (16/2/2021) lalu.
Kesan pertama adalah, di era dunia tanpa batas ini, yang menurut pemahaman awam saya adalah manusia sudah tak menghiraukan batasan tentang nilai, norma, kemanusiaan, moral, nurani, agama, dan sak panunggalane lainnya, namun masih ada penulis yang perhatian terhadap istilah yang saya sebutkan tadi.
Kesan kedua, saya menangkap ada fenomena tentang politik pendidikan dan penyematan gelar akademik yang dirasa tidak selayaknya perolehan gelar pada umumnya yang diterima oleh mahasiswa setelah menyelesaikan studi.
Kesan ketiga,
Kesan keempat anggapan masyarakat termasuk saya bahwa yang tampak pada institusi pendidikan tinggi baik swasta maupun negeri, merupakan tempat atau gudangnya ilmuwan yang beretika dan beragama dengan mengedepankan akhlak al-karimah tingkat dewa untuk menjadi the agent of change tidak terbukti. Sehingga seperti buah mojo dari luar tampak halus dan mulus ternyata setelah dibuka rasanya pahit.
Tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia kampus menjadi terusik dan memasuki tingkat ketidakpercayaan tingkat dewa. Hal yang demikian otomatislah terdapat bukti lain. Sehingga apa pun yang diomongkan akademisi sekedar teori belaka, begitu kira-kira anggapan selanjutnya.
Atas ketiga kesan tersebut mendorong saya membuat ringkasan sebagai dokumen untuk selanjutnya mengisi kamar blog paperspost.com ini supaya tidak fakum.
Jadi untuk sampai pada tujuan siapa pun pasti melalui jalan, terlepas jalan apa pun adanya yang ditempuh itu tergantung manusianya. Nah suatu fenomena memang, untuk menuju capaian gelar akademik (bahasa saya), menurut essay Ardhie Raditya ada tiga jalan dalam meraihnya.
Pertama melalui jalan kesunyian; Diperlukan juga kesabaran, ketekunan, pengetahuan, dan kasih sayang intelektual. Mereka ibaratnya pendekar dari gua hantu. Gelar doktor tak sebatas puncak pendidikan formalnya. Tapi juga pengayaan mata hati penyandangnya.
Pendidikan sarjana berorientasi pengetahuan umum, yakni mempelajari dasar keilmuan tertentu dan memahaminya. Itu sebabnya, mereka membutuhkan arahan pembimbing sebagai pegangan. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah «kaum rebahan» pendidikan. Pendidikan master setingkat di atasnya.
Pendidikannya bukan sekadar dasar keilmuan tertentu. Tapi juga bagaimana dasar keilmuan itu dibangun dan diterapkan. Pada fase ini, mereka butuh proses konstruksional. Berbeda halnya pada tingkat pendidikan doktoral.
Pada level ini, kemandirian belajarnya sebagai panggilan hidup. Mereka tak hanya dituntut fasih dasar keilmuannya. Tapi juga mengevaluasi, mengkritisi, sekaligus mengkreasikan pemikiran baru. Tetapi juga kritik pada dirinya sendiri.
Kedua jalan pertukaran sosial; Jalan pertukaran sosial. Tak sedikit orang yang menempuh studi doktoral bukan atas dasar cinta ilmu pengetahuan. Mereka yang pragmatis seperti ini biasanya punya banyak motif. Studi doktoral yang ditempuhnya, misalnya, berorientasi ekonomi dan sosial.
Baginya gelar doktor diyakini bisa menambah kemapanan ekonominya di masa depan. Padahal, pertukaran sosial seperti ini menunjukkan krisis psikologis dan struktur sosial. Di sisi lain, masyarakat di sekitarnya telah telanjur mengidap penyakit gila gelar. Pada masa itu gelar merupakan rekayasa kolonial agar bangsa jajahan tunduk kepada tuannya.
Pascakolonial, budaya gila hormat dengan rekayasa gelar-gelar terus dipelihara dan diperbarui. Itulah perilaku pejabat di instansi pemerintahan yang tak punya banyak waktu belajar.
Ketiga jalam pemberian: Gelarnya disebut doktor honoris causa atau disingkat Dr Hc. Menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013, doktor kehormatan dianugerahkan kepada orang-orang berjasa. Tetapi, akhir-akhir ini doktor kehormatan rupanya makin berwajah politis. Sebab, mereka yang dianugerahi gelar ini oleh kampus tertentu justru berlatar belakang elite politik.
Padahal, elite politik yang mendapatkan gelar kehormatan dianggap punya sejarah buruk. Meskipun gelar Dr Hc tak digunakan pada kegiatan akademik, pemberian gelar ini melukai perasaan komunitas akademik. Gus Dur dengan sentilan pedasnya di era 1990-an memelesetkan Dr Hc dengan doktor humoris causa. Gus Mus pun menyebutnya doktor honore caos.
Mereka dianggap main mata dengan penerima gelarnya. Mereka meneladani kehidupan. Mereka paham makna penderitaan. Mereka juga paham maknanya menjadi manusia yang mengerti perasaan manusia. Sekalipun tak semua menikmati mewahnya pendidikan tinggi, mereka mewarisi nilai-nilai rendah hati, adil, dan bijaksana.
Namun jauh panggang dari api, anggapan tidak sebagaimana kenyataan, halus dan lembutnya kulit luar buah mojo tak sebanding dengan rasa buahnya yang teramat pait untuk dikonsumsi.
Kesimpulannya adalah politisasi pendidikan seperti tersebut mau tidak mau akan menuai dilema. Hal itu bukan hanya menimpa kepada penerima gelar tetapi juga pemangku kepentingan kampus beserta stakeholder juga. Lha bagaimana hendak meningkatkan layanan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi jika para aktornya bermoral hebat begitu.
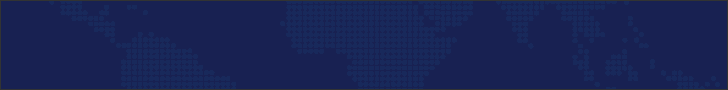

0 Response to "Fenomena Politik Pendidikan Gelar Akademik Dan Buah Mojo"
Posting Komentar
Mohon komentar yang baik untuk keharmonisan bersama